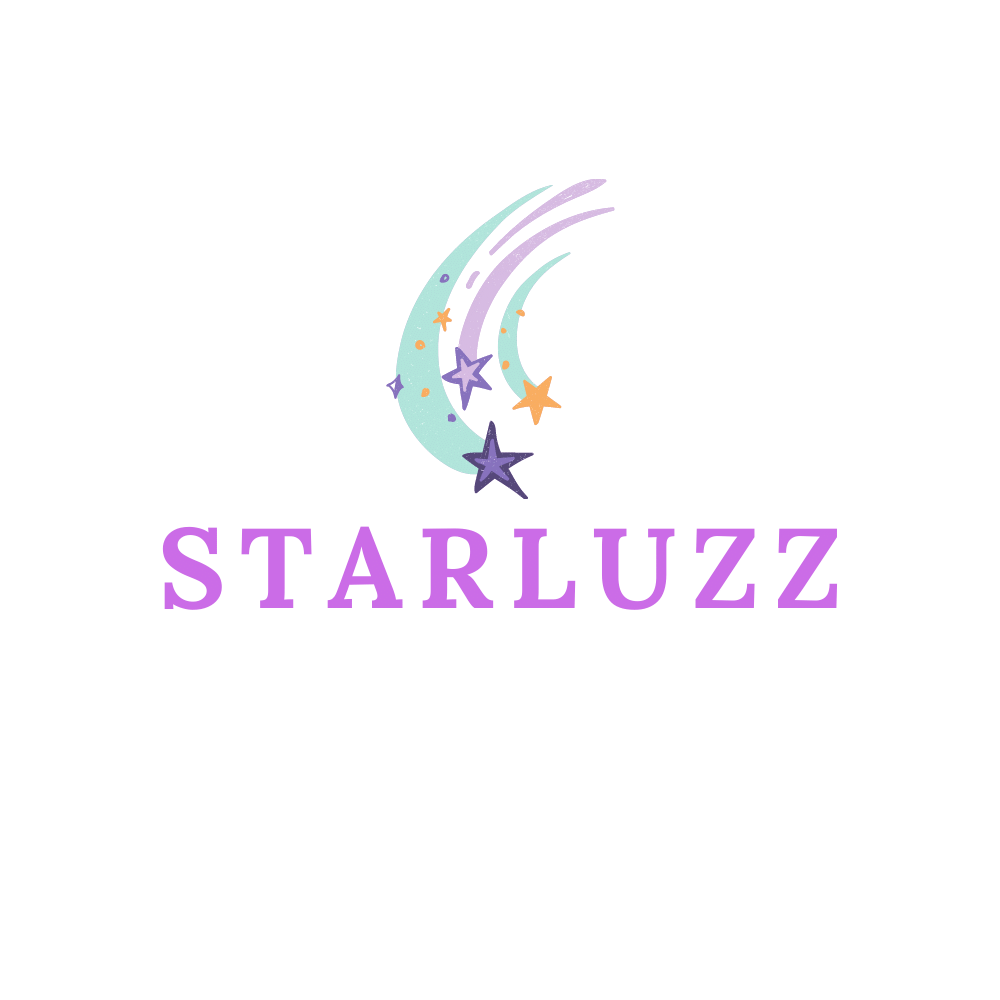Saya masih ingat dengan jelas sore itu di sebuah kafe di Yogyakarta. Saya, seorang pria Jawa yang terbiasa dengan basa-basi dan alunan bahasa yang lembut, duduk berhadapan dengan seorang wanita berambut pirang dan mata biru yang berbicara dengan aksen yang terdengar seperti musik dari film-film Hollywood. Namanya Sarah, dan dia adalah turis yang tersesat mencari galeri seni. Saya, dengan bahasa Inggris yang terbata-bata hasil kursus dan nonton film, mencoba membantunya. Siapa sangka, percakapan canggung yang dimediasi oleh Google Translate itu adalah awal dari perjalanan hidup yang tidak pernah saya bayangkan.
Hari ini, Sarah bukan lagi turis yang tersesat. Dia adalah istri saya, teman hidup saya, dan ibu dari anak-anak kami. Hidup bersama seseorang yang berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang sama sekali berbeda adalah sebuah petualangan tanpa akhir. Ini bukan sekadar tentang cinta, tetapi tentang belajar, beradaptasi, dan pada akhirnya, menciptakan dunia baru milik kami sendiri.
Babak Awal: Google Translate Sebagai Saksi Bisu
Hubungan kami di masa-masa awal adalah komedi romantis yang sesungguhnya. Komunikasi adalah tantangan terbesar sekaligus sumber tawa kami. Google Translate menjadi orang ketiga dalam hubungan kami, selalu siap sedia di ponsel untuk menerjemahkan kata-kata cinta yang rumit atau sekadar bertanya, "Kamu mau makan apa malam ini?"
Ada banyak sekali kesalahpahaman yang lucu. Suatu hari, saya mencoba menjelaskan konsep "masuk angin" kepadanya. Saya berusaha keras menerjemahkannya sebagai "the wind entered my body." Wajahnya yang bingung dan sedikit ngeri membuat saya sadar betapa banyak konsep dalam budaya kita yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, saya sering kebingungan dengan idiom-idiom bahasa Inggris. Ketika pertama kali dia berkata, "You need to bite the bullet," saya benar-benar membayangkan harus menggigit sebutir peluru.
Namun, di tengah segala keterbatasan itu, kami belajar bahasa yang lebih universal: bahasa kesabaran dan pengertian. Kami belajar membaca ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Kami menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu membutuhkan kata-kata yang sempurna. Terkadang, sebuah senyuman tulus atau genggaman tangan yang erat sudah cukup untuk mengatakan, "Aku di sini untukmu."
Perlahan tapi pasti, bahasa kami mulai menyatu. Saya menjadi lebih percaya diri dengan bahasa Inggris saya, dan dia dengan antusias belajar Bahasa Indonesia. Mendengarnya pertama kali memesan "nasi goreng satu, pedas sedikit" dengan logatnya yang khas adalah salah satu momen paling membahagiakan bagi saya.
Dapur Kami: Pertemuan Sambal dan Shepherd’s Pie
Jika ada satu tempat di mana dua budaya benar-benar bertemu (atau terkadang bertabrakan), itu adalah di dapur. Saya dibesarkan dengan keyakinan bahwa makanan tanpa sambal adalah makanan yang hambar. Sarah, di sisi lain, tumbuh dengan kentang panggang, pai daging, dan saus gravy.
Awalnya, ini adalah sebuah negosiasi. Dia mencoba masakan ibu saya dengan hati-hati, matanya berair karena pedasnya rendang, tetapi kemudian dengan jujur berkata, "This is the most amazing thing I’ve ever tasted!" Saya, di sisi lain, belajar untuk menghargai sarapan dengan sereal dan susu, atau makan malam Natal dengan kalkun panggang.
Dapur kami kini menjadi laboratorium fusi budaya. Kami menciptakan hidangan "gado-gado" kami sendiri: spageti dengan bumbu balado, atau pizza dengan topping rendang. Anak-anak kami tumbuh dengan palet rasa yang kaya, mereka bisa menikmati semangkuk soto ayam di pagi hari dan makan makaroni keju di malam hari tanpa merasa aneh. Makanan, bagi kami, bukan lagi sekadar pengisi perut, melainkan cara kami merayakan keberagaman yang ada di dalam keluarga kecil kami.
Menavigasi Norma Sosial dan Keluarga Besar
Membawa Sarah bertemu dengan keluarga besar saya adalah sebuah pengalaman tersendiri. Konsep keluarga di Indonesia sangat komunal. Acara kumpul keluarga bisa melibatkan puluhan orang, dari kakek-nenek hingga sepupu jauh. Bagi Sarah yang terbiasa dengan pertemuan keluarga yang lebih kecil dan intim, ini adalah sebuah culture shock.
Saya harus menjadi penerjemah budaya. Saya menjelaskan kepadanya tentang pentingnya basa-basi, mengapa semua orang bertanya "kapan punya anak?" (meskipun baru menikah seminggu), dan tradisi sungkem saat Lebaran. Di sisi lain, saya juga harus menjelaskan kepada keluarga saya mengapa istri saya lebih suka berbicara langsung ke intinya, mengapa dia merasa tidak nyaman dengan pertanyaan yang terlalu pribadi, dan mengapa dia butuh "me time" atau ruang untuk sendiri.
Butuh waktu, tetapi keluarga saya akhirnya jatuh cinta pada kepribadian Sarah yang tulus dan ramah. Mereka melihat bagaimana dia berusaha keras belajar bahasa dan adat istiadat. Momen ketika nenek saya, yang tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali, bisa tertawa bersama Sarah sambil berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan senyuman, adalah bukti bahwa ikatan keluarga bisa melampaui batas bahasa.
Sebaliknya, saya juga belajar banyak dari budayanya. Saya belajar tentang pentingnya kemandirian, komunikasi yang terbuka dan jujur dalam sebuah hubungan, serta bagaimana menghargai batasan pribadi. Dia mengajari saya bahwa mengatakan "tidak" itu bukan berarti tidak sopan, dan bahwa mengungkapkan perasaan secara langsung bisa mencegah kesalahpahaman di kemudian hari.
Menciptakan Bahasa Kami Sendiri: "Bahasa Gado-Gado"
Setelah bertahun-tahun bersama, kami telah menciptakan bahasa ketiga, sebuah bahasa hibrida yang hanya kami berdua yang mengerti. Kami menyebutnya "Bahasa Gado-Gado." Dalam satu kalimat, kami bisa dengan mudah mencampurkan Bahasa Indonesia dan Inggris.
"Sayang, can you please ambilkan the remote? It’s on the meja."
"Of course, dear. Habis ini we watch that new series, okay?"
Bahasa ini adalah simbol dari hubungan kami. Ia tidak murni Indonesia, juga tidak murni Inggris. Ia adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang kami bangun bersama dari potongan-potongan dunia kami masing-masing. Bahasa ini adalah cerminan dari identitas keluarga kami yang unik.
Anak-anak kami tumbuh menjadi penutur asli "Bahasa Gado-Gado" ini. Mereka adalah jembatan hidup antara dua dunia. Mereka bisa dengan lancar beralih dari berbicara Bahasa Indonesia dengan kakek-nenek mereka, ke Bahasa Inggris saat berbicara dengan keluarga ibunya melalui video call. Melihat mereka tumbuh dengan dua bahasa dan dua budaya adalah anugerah terbesar. Mereka memiliki jendela yang lebih luas untuk melihat dunia, pikiran yang lebih terbuka, dan pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman.
Lebih dari Sekadar Kata-kata
Memiliki istri berbahasa Inggris telah mengubah cara saya memandang dunia. Ini bukan hanya tentang belajar bahasa baru, tetapi tentang membuka pikiran saya terhadap cara pandang, cara berpikir, dan cara merasakan yang berbeda. Saya belajar bahwa ada banyak cara untuk menjadi benar, banyak cara untuk hidup, dan banyak cara untuk mencintai.
Tentu, ada tantangan. Ada hari-hari di mana kami merasa lelah karena harus terus-menerus menerjemahkan, tidak hanya kata-kata tetapi juga konteks budaya. Ada momen di mana kami merindukan kemudahan berbicara dengan seseorang yang sepenuhnya memahami latar belakang kami tanpa perlu penjelasan.
Namun, semua tantangan itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekayaan yang kami dapatkan. Hubungan kami adalah bukti nyata bahwa cinta tidak mengenal batas geografi, budaya, atau bahasa. Cinta adalah bahasa itu sendiri—bahasa universal yang diucapkan melalui kesabaran, empati, tawa, dan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh bersama.
Setiap hari, saya bersyukur atas sore itu di kafe Yogyakarta. Sore di mana seorang pria Jawa yang pemalu bertemu dengan seorang wanita asing yang pemberani. Kami memulai dengan bahasa yang terpatah-patah, tetapi kami membangun kehidupan dengan cinta yang utuh. Dan dalam dunia kecil kami yang penuh warna, kami telah menemukan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan benang-benang yang menenun permadani kehidupan kami menjadi jauh lebih indah.